Jalan-jalan | Faris Alfadh
Sejak menginjakkan kaki di Tokyo, Jepang, untuk pertama kalinya pertengahan September lalu, setiap akhir pekan atau hari libur lainnya, saya selalu menyempatkan diri berkunjung ke tempat-tempat wisata, atau sekedar menyapa sudut-sudut kota yang masih terasa asing. Hal ini saya lakukan selain karena hari itu memang libur (Senin hingga Jum’at biasanya saya habiskan di perpustakaan kampus Tokyo University of Foreign Studies, ataupun mengunjungi beberapa Professor di kampus lain), tempat-tempat tersebut juga menawarkan mozaik tersendiri sebagai salah satu cara menikmati atmosfir kota Tokyo—salah satu kota tersibuk di dunia, sekaligus terpadat penduduknya di Jepang.
Di Tokyo, tidak terlalu sulit mencari tempat berakhir pekan. Ada banyak tempat wisata dan juga public park yang bisa dikunjungi. Tempat-tempat di mana orang bisa berjalan santai bersama sanak famili, teman, ataupun kekasih. Tempat-tempat wisata diakronis seperti Shinso-ji Temple, Imperial Palace, Yasuki Shrine, Kamakura, bisa menjadi pilihan berplesir. Selain itu, beberapa museum dan public park juga cukup banyak. Bagi anak-anak muda dan para sosialita, tempat-tempat nongkrong gaul seperti Shibuya, Harajuku, Akihabara, Ueno, tentu tidak asing lagi. Nah akhir pekan lalu, Sabtu 3 Oktober, saya memilih berkunjung ke Tokyo National Museum (tidak jauh dari Ueno Park).
Saya menyambut senang ajakan Mba Erika beberapa hari sebelumnya, karena hari itu kebetulan diadakan acara kebudayaan yang cukup istimewa. Acara tersebut, menurut penyelengara, hanya diadakan dua kali dalam satu tahun. Sebenarnya acara tersebut diperuntukkan untuk menyambut bulan purnama pertama di musim gugur. Namun karena hari itu juga bertepatan dengan hari kemerdekaan Korea Selatan dan bersatunya Jerman Barat dan Timur, maka acara tersebut pun sengaja diberi tema “Cultural Exchange Day for Foreign Students”.
Selain itu, yang membuat kami dengan senang hati datang tentu saja karena acara hari itu free of charge alias gratis khusus bagi mahasiswa asing: cukup dengan memperlihatkan kartu mahasiswa. Bagi pelancong asing atau mahasiswa Jepang, tetap harus bayar. Tentu saja ini menyenangkan bagi kami, para perantau ilmu yang menggantungkan hidup dari beasiswa, karena bisa menghemat pengeluaran. Biasanya acara semacam ini bisa dikenakan charge 400-500 yen per acara. Nah jika mengikuti semua acara, bisa dihitung berapa yen yang harus kami keluarkan.
Di kota seperti Tokyo, kebiasaan berkunjung ke Museum (mungkin juga tidak jauh berbeda dengan kota-kota lainnya di negara maju), sudah jamak dilakukan. Tentu saja hal ini berbeda dengan yang kita alami di Indonesia. Jika anak-anak muda di Indonesia amat jarang berkunjung ke Museum, maka di Tokyo hal itu justru cukup menyenangkan. Hal ini bisa kita maklumi, karena Museum di Tokyo juga dikondisikan sebagai situs wisata yang sangat comfortable. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana Museum masih belum memadai, koleksi benda-benda sejarah yang disediakan juga terkesan tidak menarik lagi karena tak cukup terawat.
Pengalaman akhir pekan kemarin bisa dibilang sangat menyenangkan. Banyak hal yang bisa saya ketahui hanya dari mengunjungi Museum selama satu hari itu. Bagi yang belajar sastra ataupun sejarah kebudayaan Jepang, tentu saja benda-benda yang ada di Museum tersebut sedikit banyak familiar. Nah bagi yang tidak, seperti saya misalnya, yang belajar Hubungan Internasional, isu-isu politik lah yang lebih kami akrabi.
Beberapa benda sejarah, baik yang berasal dari zaman pra sejarah hingga abad modern, sedikit menggambarkan bagaimana peradaban dan kebudayaan Jepang dibangun. Yang menarik adalah, banyak hal sederhana yang ternyata sangat menarik diketahui. Misalnya, Jepang yang di akhir abad ke-19 dan awal abad 20 begitu kuat secara militer, hingga pernah menjajah sebagian wilayah di negara-negara Asia Timur seperti Korea dan China, serta negara Asia Tenggara seperti Indonesia, ternyata dulu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan China dan Korea.
Pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9, misalnya, Jepang bahkan banyak mengirmkan pemuda-pemudanya untuk belajar ke China. Pada zaman inilah Jepang mengadakan pembaharuan kebudayaan besar-besaran. Salah satunya dengan meniru berbagai pranata dari China. Saya juga jadi tahu beberapa hal sederhana lainnya. Ternyata orang Jepang juga sudah megenal cobek (untuk mengulak sambal) sejak zaman pra sejarah. hehehe… Sebelumnya, di Jepang tidak ada yang namanya kuda. Kuda baru dikenal ketika interaksi dengan China mulai terjadi. Begitu juga dengan besi. Saya menduga (bisa jadi dugaan saya keliru), hal ini dikarenakan peradaban China lebih dahulu maju, sehingga beberapa elemen penting, seperti penemuan besi, di bawa dari China.
Namun demikian, di zaman Heian (kalau tidak salah sekitar abad ke-11), Jepang mulai menciptakan budaya khasnya sendiri, tentu saja masih menggunakan rujukan dari China. Salah satu yang dianggap penting adalah tulisan Kana . Namun di zaman Edo (wilayah yang dulu disebut Edo kini adalah Tokyo), sekitar abad ke-16, Jepang kemudian menutup diri dari segala pengaruh asing untuk selama kurun waktu tiga abad. Saya menduga, di periode inilah mulai banyak muncul kebudayaan asli Jepang. Jika selama ini kita sangat mengenal Kimono atau sering juga disebut Yukatta, pakaian tradisional Jepang, nah pakaian ini diyakini murni berasal dari kebudayaan Jepang.
Dari seluruh agenda yang saya ikuti di Museum akhir pekan lalu, hal yang paling menarik dan sangat berkesan bagi saya adalah “Japanese Tea Ceremony Performances”, atau upacara minum teh. Selain karena upacara ini menjadi salah satu ciri khas dari budaya Jepang, kesempatan untuk mengikutinya pun sangat jarang.
Upacara minum teh kemarin diadakan di “Okyokan Teahouse”, sebuah rumah tradisional Jepang yang terletak di taman belakang Museum, dikelilingi pepohonanan sakura yang rindang dan apik (bunga sakuranya masih belum mekar). Puri sederhana yang ada di dalamnya, mengingatkan saya pada rumah-rumah khas Jepang yang ada di film Oshin, film serial yang kerap saya tonton bersama Ibu ketika masih kecil dulu. Rumah kayu dengan pintu didorong ke samping, serta dinding-dindingnya yang terbuat dari bahan kertas tebal putih dengan aneka corak lukisan pohon sakura. Dan yang lebih menyenagkan lagi adalah, ternyata Okyokan Teahouse tersebut sudah digunakan sebagai tempat upacara minum teh oleh para bangsawan sejak zaman Edo, yaitu sekitar tahun 1600.
Saat itu syahdan, saya seolah membayangkan berada di zaman ketika Musashi masih hidup. Mengikuti langsung bagaimana seorang perempuan dengan pakaian Kimono lengkap menyajikan teh hijau khas Jepang yang sebelumnya sudah diracik sedemikian rupa dengan ritual-ritual khusus. Kita juga diajarkan cara meminum teh dengan elegan, yakni memutar mangkuknya dua kali ke arah kanan sebelum meminumnya. Dan sesudahnya, mangkuk pun harus diputar dua kali ke arah yang berlawanan untuk mengembalikan ke posisi semula. Bagi yang baru pertama kali mencoba teh hijau khas Jepang, mungkin akan terasa sedikit pahit. Namun setelah mencoba beberapa kali, maka sensasi teh hijau justru semakin terasa ma’nyus.
Kami cukup beruntung, sebenarnya, bisa mengikuti upacara minum teh tersebut. Karena acara tersebut hanya dibatasi bagi 30 orang saja. Bagaimana kami bisa masuk? Hah, tentu saja setelah kami mengantri selama satu setengah jam untuk mendapatkan tiket sebelum acara dimulai. Namun demi sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya, menunggu pun tak sedikitpun terasa menyebalkan.
Seperti yang selalu saya yakini, salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup adalah ketika kita bisa bertemu dengan banyak orang, banyak tempat, banyak budaya, dan (tentu saja) banyak makanan. Namun sayang, untuk urusan yang saya sebut terakhir, hanya beberapa jenis kuliner saja yang bisa cocok di lidah. hehehe.
Mahasiswa Hubungan Internasional UMY Raih Prestasi di Ajang SUKARABIC FEST
VII 2025 Tingkat Asia Tenggara
-
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY), Abdulsalam Saad, kembali menorehkan prestasi membanggakan
sete...
1 month ago
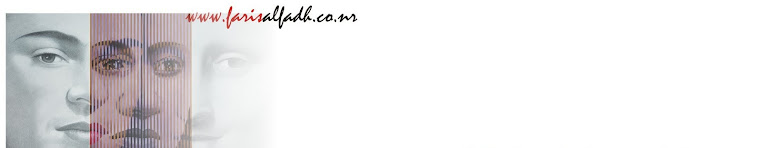





akhirnya posting juga setelah sekian lama :-)
ReplyDelete