
Catatan | Faris Alfadh
Bagi yang masih optimis dengan sistem demokrasi kita, hari ini menjadi penting karena untuk ketiga kalinya pemilihan umum diadakan pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Bisa jadi hari ini mereka bagun lebih pagi dari biasanya. Membaca koran ditemani secangkir teh panas, beberapa saat kemudian mungkin bersiap-siap menuju TPS untuk memberikan hak pilih.
Namun bagi mereka yang bermuram durja menyongsong pemilu 2009, atau sedikit pesimis, tidak ikut memilih alias golput adalah pilihan paling rasional. Ketimbang menanggung resiko kecewa karena salah menyealurkan dukungan, mereka merasa lebih baik tak berpartisipasi dan memanfaatkan libur panjang pekan ini untuk kegiatan lain, mungkin berlibur ke luar kota bersama keluarga. Bagi mereka yang di rumah saja, bisa jadi memilih bangun agak telat.
Adanya kemungkinan banyaknya pemilih yang tidak akan menggunakan hak pilihnya, memang sudah diprediksi banyak kalangan. Jauh-jauh hari dengan tekad bulat mereka telah mengibarkan bendera putih. Dugaan sementara: suara golput akan lebih banyak ketimbang jumlah suara sang pemenang nanti. Banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (padahal mereka ingin memilih) juga menjadi persoalan lain.
Saya akui, memilih untuk tidak memilih juga sebuah pilihan. Dan yang paling penting, itu tidak melanggar hukum. Dalam sistem demokrasi modern hal ini wajar-wajar saja. Bahkan di beberapa negara yang iklim demokrasinya terbiang mapan, seperti AS, fenomena golput juga banyak dijumpai. Karena itu, sikap sebagian besar masyarakat kita yang (berniat) golput tentu saja bisa dimaklumi, terutama jika melihat sistem kepartaian, gelagat anggota partai, hingga ulah para caleg yang ikut dalam pemilu kali ini. Semuanya memang mengecewakan!
Bayangkan saja, ada puluhan partai politik yang menjadi peserta pemilu namun tak pernah jelas program dan ideologinya. Sampai-sampai, saya—dan mungkin juga anda, kesulitan untuk membedakan satu partai dengan partai lainnya karena ketakjelasan tadi. Banyaknya partai politik ini tidak terlepas dari konstelasi politik Indonesia yang masih dicerminkan polarisasi elit, bukan polarisasi politik rakyat. Karena itu tidak heran jika suatu ketika ada seorang elit yang kecewa dengan partainya lalu keluar dan mendirikan partai sempalan. Itulah yang terjadi dengan partai-partai yang ada sekarang.
Mungkin ada yang bertanya, kenapa parati-partai gurem ini sekilas memiliki massa yang cukup saat kampanye terbuka kemarin? Eits, jangan terkecoh! Bisa jadi yang ikut pawai di jalan-jalan pada hari kampanye itu hanya tenaga bayaran. Dan bisa jadi juga mereka adalah orang-orang yang justru tak hendak memilih.
Dulu, di zaman Aristoteles masih hidup, konon ia tidak terlalu respect dengan yang namanya demokrasi. Baginya demokrasi adalah sistem politik yang buruk, karena memberikan kesempatan bagi siapa saja tampil sebagai memimpin, termasuk masyarakat yang tidak terdidik sekalipun. Karena itu ia lebih sepakat jika negara sebaiknya dipimpin oleh para filsuf saja. Suatu saat, demikian keyakinannya, demokrasi akan memberikan kesempatan bagi lahirnya orang-orang bodoh untuk berkuasa. Mungkin benar, mungkin juga keliru. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat fenomena yang mengkhawatirkan itu. Berapa banyak anggota parlemen yang masuk bui karena suap dan korupsi? Hampir semua partai politik “lama”, yang sudah punya wakil di DPR, kadernya tersandung kasus korupsi. Bahkan para caleg yang bertarung dalam pemilu 2009 ini tidak sedikit yang bermasalah: Ada yang kedapatan menjual ganja, mencuri motor, hingga terpergok di panti pijat. Tentu saja ini memalukan! Siapa yang mau memilih calon angota legislatif macam ini? Belum lagi fenomena munculnya caleg “siluman”: mereka yang sebelumnya tak pernah nongol di satu daerah, eh tiba-tiba saja namanya muncul dalam daftar caleg dari daerah tersebut.
Karena itu, wajar jika sebagian masyarakat menganggap semua partai politik sama saja: tukang ngibul dan obral janji. Kampanye pun hanya sebagai ajang tipu-tipu. Belum lagi ekses buruknya: ruas jalan, sudut kota, rimbunan pohon, tiang listrik, WC umum, hingga tembok tetangga, semuanya disesaki stiker, spanduk dan pamphlet para caleg dan parpol. Karena itu, ketimbang ikut mencontreng, mereka yang kecewa lebih memilih untuk istirahan di rumah menikmati libur sambil tidur siang. Bahkan ada yang membuat lelucon dengan mengatakan: “Tidur siang yang paling enak adalah pada hari pencontrengan.” Hmm…
Dengan tetap menghormati pilihan mereka yang golput, namun bagi saya, demokrasi yang masih semrawut ini justru bisa ditata lebih baik jika kita tetap memberikan hak pilih. Menurut saya, sikap tidak ikut memilih justru ikut mencederai kualitas demokrasi. Demokrasi memang bukan sistem politik paling sempurna, tetapi untuk saat ini demokrasi adalah pilihan paling masuk akal bagi kita. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendasarkan pilihannya pada pertimbangan-pertimbangan rasonal, bukan emosional ataupun irasional.
Sikap sinis dan skeptis tentu boleh-boleh saja, tetapi sebaiknya hal itu jangan sampai menghalangi kita untuk melihat banyak hal positif yg dicapai negeri ini sejak era reformasi. Walupun di sana sini terlihat masih centang perenang, namun kita mendapatkan banyak berkah dari demokrasi. Demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan terutinggi terletak pada aspirasi mayoritas masyarakat. Karena itu, tugas untuk menata dan memperbaiki kualitas demokrasi juga ada di pundak orang ramai. Demokrasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa dikawal.
Salah satu kelebihan dari sistem demokrasi adalah ia tidak anti kritik. Karena bagimanapun hanya dengan kritiklah kualitas demokrasi bisa terus diperbaiki. Tentu saja tidak instan dan memerlukan jalan terjal untuk itu. Namun perlu diingat, Indonesia baru benar-benar menghirup harumnya kebebasan dan menikmati demokrasi dalam sepuluh tahun terakhir. Sangat tidak adil jika harus dibandingkan dengan kemapanan demokrasi yang sudah diraih oleh negara-negara maju lainnya, yang bahkan untuk sampai ke situ memerlukan kurun waktu ratusan tahun.
Dalam pemilu 2009 ini, beberapa perbaikan mekanisme yang sebelumnya masih terlihat centang perenang pada pemilu 2004, sedikit demi sedikit mulai terlihat. Misalnya, tanggung jawab masyarakat akan semakin besar atas kualitas wakil rakyat karena Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan perubahan mekanisme penentuan peringkat caleg yang awalnya berdasarkan nomor urut sekarang menjadi jumlah suara terbanyak. Dalam jangka panjang, hal ini akan semakin memperbaiki kualitas calon. Memang terdapat beberapa caleg yang kualitasnya tidak jelas, tetapi tidak sedikit juga yang masih kualified.
Dalam pemilu kali ini, misalnya, jumlah caleg yang berpendidikan sarjana meningkat dibanding pemilu 2004. Berdasarkan pendataan Litbang Kompas, sekitar 80 persen kandidat anggota DPR dalam pemilu 2009 adalah sarjana. Hampir 5.000 orang dari 11.225 adalah lulusan sarjana strata 1, 1.599 orang lulusan pascasarjana, dan 281 orang doktor. Memang kenaikan drastis jumlah sarjana ini tidak serta-merta menggambarkan cerlangnya prospek perbaikan kualitas kinerja caleg, tetapi paling tidak mulai ada perbaikan kualitas personal.
Banyaknya caleg yang kualitasnya tidak karuan memang tidak terlepas dari mekanisme seleksi partai yang masih buruk. Kualifikasi calon belum diangap sebagai pertimbangan determinan. Kebanyakan partai masih mendasarkan rekrutmen caleg-nya pada nilai popularitas dan sejumlah uang, bukan pada keahlian dan integritas. Karena itu dalam pemilu 2009 ini banyak kita temukan fenomena selebritas dan pengusaha masuk dalam bursa caleg. Mereka yang belum punya pengalaman sama sekali tidak jadi soal. Karena bisa ditraining kilat dalam beberapa bulan. Inilah penyakit yang disebut Eep Saefulloh Fatah sebagai “krisis seleksi”. Hanya satu obatnya, kata Eep: kita, para pemilih, pandai-pandailah memilih yang terbaik di antara yang buruk. Dengan kata lain, ia menawarkan bahwa krisis seleksi tersebut hanya bisa siperbaiki lewat mekanisme eleksi.
Karenanya, dalam konteks tersebut, menggunakan hak pilih dengan ikut mencontreng menjadi sesuatu yang amat mahal harganya. Karena hanya dengan demikian kualitas demokrasi kita bisa diperbaiki. Nah, bagi anda yang berniat mencontreng hari ini, atau masih limbung menentukan pilihan, ada baiknya mengikuti saran majalah Tempo edisi minggu lalu, yakni dengan memperhatikan terlebih dahulu latar belakang partai, begitu juga rekam jejak para pendiri dan tokohnya, serta sepak terjang mereka selama ini. Jika sreg, ha, boleh lah anda pilih. Tetapi “jika setelah itu hati belum juga mantap memilih, apa boleh buat, mari tidur siang saja.”
* Judul tulisan ini terinspirasi oleh salah satu tulisan dalam majalah Tempo edisi 30 Maret-5 April 2009, yang berjudul “Bibi Teliti atawa Tidur Siang Saja”.
Mahasiswa Hubungan Internasional UMY Raih Prestasi di Ajang SUKARABIC FEST
VII 2025 Tingkat Asia Tenggara
-
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY), Abdulsalam Saad, kembali menorehkan prestasi membanggakan
sete...
1 month ago
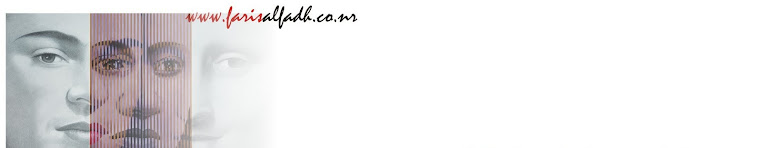



Yah, Yah, kemarin dengan terpaksa saya tidak memilih nyontreng ataupun tidur. Tapi milih ngenet seharian.
ReplyDeleteKarena sistem buruk kayak gini jadinya yeah.., terpaksa deh...
Terimakasih atas kunjungannya, kawan :-)
ReplyDeleteterimakasih atas kunjungannya kawan :-)
ReplyDeleteterimakasih atas kunjungannya kawan :-)
ReplyDelete