Apa yang saya ingat pada hari ini adalah sebuah momen di tahun 619 M, ketika Muhammad, Nabi yang Agung, dengan segala keteguhan jiwanya menunjukkan kepada (semua) manusia bahwa jalan kemuliaan tidak mudah untuk diraih dan amat panjang untuk ditempuh.
Sepanjang hari-hari pada tahun itu, setelah kematian Khadijah–istri Nabi yang begitu ia cintai, Mekah tak lagi ramah bagi pengikut Muhammad. Kaum Quraisy, yang menguasai hampir seluruh gurun kota itu, melihat sebuah ancaman pada pengikut Muhammad yang kian hari bertambah banyak. Para penganut awal (as-sabiqun al-awwaluun) agama Tauhid ini pun menghadapi beragam cobaan, ancaman, hingga konspirasi.
Syahdan, semuanya berawal ketika para pemuka Quraisy mengadakan pertemuan di sebuah majelis. Setelah melalui perdebatan panjang, mereka pun akhirnya menyetujui sebuah konspirasi yang dikemukakan Abu Jahal. Tujuannya satu: membunuh Muhammad!
Dalam pertemuan tersebut diptuskan bahwa setiap kabilah akan mengutus seorang pemuda yang kuat. Pada saat yang ditentukan, semua pemuda pilihat itu harus bersama-sama menikam Muhammad hingga darahnya mengucur dan mengenai semua (utusan) kabilah. Mereka yakin, hanya dengan cara inilah keyakinan Muhammad, yang menurut mereka bisa mengancam ajaran agama leluhur mereka, bisa dihentikan.
Namun Tuhan punya rencana lain. Pada saat bersamaan, Jibril pun datang menemui Nabi dan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Sore itu, Nabi langsung menemui Abu Bakar di rumhanya–sebuah kunjungan yang tidak biasa, tentunya.
“Allah telah mengizinkan aku untuk meninggalkan kota ini dan berhijrah,” kata Nabi.
“Bersama denganku?” Tanya Abu Bakar.
“Ya, bersamamu,” jawab Nabi kemudian.
Sejak itu, kita mengenang perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai sebuah ijtihad besar Rasulullah beserta para sahabat dalam menegakkan apa yang dinamakan “Iman”. Kita juga belajar satu hal darinya: bahwa kemuliaan dan kebahagiaan iman tidak ditempuh dengan jalan yang mudah. Ia tidah hanya butuh perjuangan dan pengorbanan, tetapi juga keyakinan untuk berserah.
Tak terbayang, misalnya, para as-sabiqun al-awwaluun kala itu, harus berjalan di atas gurun yang gersang dalam kalut, disirami panas teriknya matahari serta diselimuti dinginnya malam. Berjalan menyusuri gunung-gunung berbatu, terbayang ancaman dan rasa takut. Bahkan Abu Bakar sendiri, sahabat Nabi yang dijuluki as-siddîq itu, mengalami ketakutan yang sangat, ketika harus bersembunyi di sebuah Gua bernama Hira bersama Nabi. Sampai-sampai Nabi menghibur Abu Bakar dengan berkata: “Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”.
Kata “Hijrah”, menurut Quraish Shihab, seringkali digunakan untuk mengistilahkan perpindahan suatu individu/kaum dari satu hal yang sifatnya buruk kepada hal lain yang sifatnya baik. Pengertian ini berlaku kepada kegiatan pindah tempat maupun pindah kelakuan. Selain contoh hijrahnya Nabi, rasa penyesalan serta taubat juga bisa dikategorikan sebagai upaya (ber)hijrah, bertekad menuju pada kondisi yang lebih baik.
Bagi saya, “hijrah” tentu bukan hanya sebatas perpindahan menuju resolusi yang lebih baik, tetapi sekaligus menyadari bahwa kehendak berubah (hijrah) harus sudah ada sejak dalam jiwa dan pikiran kita, apalagi perbuatan.
Orang selalu bilang, tahun depan harus lebih baik dari sebelumya. Namun sungguh, apa yang sebenarya anda cari dalam hidup ini? Ramai orang menjawab: kebahagiaan! Tetapi ingatlah bahwa kebahagiaan tidak akan menyapa dengan sendirinya, tanpa adanya tekad untuk berevolusi-tahap demi tahap (berhijrah).
Dalam The Bucket List, yang diperankan oleh Jack Nicholson dan Morgan Freeman, ada sebuah dialog yang menarik. Konon, Mesir kuno punya kepercayaan indah tentang kematian. Ketika jiwa manusia akan memasuki surga, para dewa akan menanyakan dua pertanyaan. Jawaban mereka menentukan apakah mereka diterima atau tidak di surga:
Sudahkah kau menemukan kebahagiaan dalam hidupmu? Apakah kehidupanmu memberikan kebahagiaan bagi orang lain?
Sebuah fragmen penuh metaphor. Tetapi bukankah Nabi Muhammad telah memberikan jawaban itu? “Khaerun nâs anfa’uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain,” kata beliau. Bahwa kebahagiaan tidak mungkin diraih tanpa membagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Ya, hidup tanpa menyisakan jejak kebahagiaan bagi orang lain, sesungguhnya tidak memiliki arti apa-apa.
Dalam hidup, rasanya sulit memahami kehidupan seseorang. Ada yang bilang ia bisa diukur dengan banyaknya orang yang ditinggalkan. Ada yang bilang kehidupan sesorang bisa diukur dari imannya. Beberapa juga bilang dengan cinta. Maka bagi saya sederhana saja: ia diukur dari sejauh mana sesorang mampu meraih dan membagi kebahagiaan!
Apa yang saya ingat pada hari ini adalah sebuah momen di tahun 619 M, ketika Muhammad, Nabi yang dimuliakan, dengan segala keteguhan jiwanya menunjukkan kepada kita semua bahwa jalan kebahagiaan ternyata tidak mudah untuk diraih dan amat panjang untuk ditempuh.
image from here
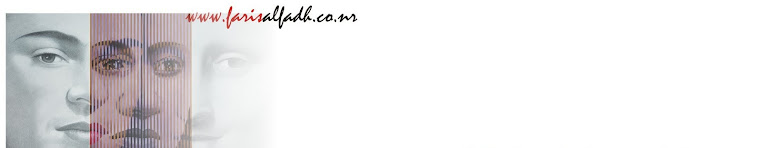




No comments:
Post a Comment