Esai | Faris Alfadh
 Saya selalu percaya, hal-hal yang tidak kita pilihlah yang membentuk diri kita: keluarga, lingkungan, kota, bahkan bangsa. Seperti yang diucapkan Casey Affleck dalam Gone Baby Gone, orang-orang bangga akan hal tersebut, seolah-olah itu hal yang mereka capai.
Saya selalu percaya, hal-hal yang tidak kita pilihlah yang membentuk diri kita: keluarga, lingkungan, kota, bahkan bangsa. Seperti yang diucapkan Casey Affleck dalam Gone Baby Gone, orang-orang bangga akan hal tersebut, seolah-olah itu hal yang mereka capai.
Tetapi bagi anak-anak muda yang hidup di awal abad 20, di sebuah bangsa yang bernama Hindia Belanda, ada kesaksian sekaligus harapan.
Harapan itu muncul dari sebuah nilai yang diperjuangkan kaum muda. Solidaritas yang dibentuk dari latar belakang yang sama sebagai warga jajahan mengakhiri semua sekat yang ada: daerah, suku, warna kulit, dan agama. Memang, “bangsa Indonesia” adalah sebuah entitas yang hanya bisa dibayangkan kala itu. Sebuah Imagined Communities, kata Benedict Anderson. Mungkin seperti ruang kosong untuk sebuah cita-cita.
Namun di tahun-tahun itu, ada semangat yang menyeruak dan tak lagi hampa. Di Belanda, para mahasiswa Hindia ini kemudian membentuk Perhimpunan Indonesia. Di tanah air, para anak muda yang rata-rata berumur 20-an tahun ini menjadi anggota berbagai perkumpulan yang bersifat kedaerahan. Ada Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks, Jong Ambon, Kaoem Betawi, Pelajar Minahasa, dan masih banyak lagi. Belum lagi organisasi politik semacam Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia.
Tahun 1925 adalah tongak penting dalam pergerakan bangsa Indonesia, ketika Perhimpunan Indonesia (di Belanda) menerbitkan Manifesto Politik. Banyak yang meyakini ini lebih fundamental daripada Sumpah Pemuda 28 Okotober 1928. Karena untuk pertama kalinya mereka dengan tegas berbicara tentang tiga prinsip dasar: unity (persatuan), fraternity (kesetaraan),dan liberty (kemerdekaan).
Kemerdekaan, kesetaraan, dan persatuan membuat mereka memiliki imajinasi yang sama akan sebuah bangsa. Identitas kedaerahanpun mulai ditingalkan dalam manifesto yang kental dipengaruhi semangat revolusi Prancis yang meruak-ruak kala itu: liberte-egalite-fraternite.
Gaung manifesto dengan cepat menjadi bahan diskusi dan mempengaruhi perkumpulan pemuda di tanah air. Nama-nama pemuda seperti Mohammad Tabrani, Muhammad Yamin, Bahder Djohan, Sumarto, Jan Toule Soulehuwij, Paul Pinontoan, adalah para pejuang awal kemerdekaan yang tergerak olehnya. Mereka kemudian menggagas Kongres Pemuda I di Jakarta, yang menjadi cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda.
Dua tahun kemudian, 1928, diadakan Kongres Pemuda II yang juga bertempat di Jakarta. Berlangsung di tiga tempat, sidang kemudian ditutup di Gedung Kramat Raya 106. Hasilnya? Lahirlah keputusan yang sangat penting dalam sejarah kebangkitan bangsa Indoneisa, yakni Sumpah Pemuda. Di area itu pula untuk pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya, walaupun hanya dilantunkan secara instrumental oleh penggubahnya, W.R. Soepratman, karena khawatir terjadi keributan dengan polisi Belanda lantaran syair lagu itu banyak mengandung kata “Indonesia” dan “merdeka”..
80 tahun berlalu setelah sumpah itu diucapkan. Sumpah yang tak kan mengungkit lagi persoalan perbedaan suku, warna kulit, dan agama, karena semuanya melebur menjadi satu tanah air, bangsa, dan bahasa.
Mungkin tak ada yang mengira bahwa apa yang sitegaskan sekumpulan pemuda 80 tahun silam itu sesuatu yang amat berharga. Karena lebih dari sekeder definisi, ia adalah hasrat untuk merdeka–tak lagi dijajah. Ya, begitulah. Seperti kata Renan, sebuah bangsa lahir dari “hasrat buat bersatu”, tapi seperti halnya tiap hasrat, ia tak akan sepenuhnya terpenuhi dan hilang. Hidup tak pernah berhenti kecuali mati.
Adakah Sumpah Pemuda selesai sebagai tonggak sejarah? Berhasilkan ia sebagai fondasi Indonesia yang kukuh?
Tentu tak semudah itu menjawabnya. Karena bangsa adalah sejarah panjang yang entah sampai kapan, dan (berakhir) di mana. Bangsa adalah kaki langit, kata Goenawan Mohamad. Impian yang mustahil, sulit, tapi berharga untuk disimpan dalam hati. Sebab ia impian untuk merayakan sesuatu yang bukan hanya diri sendiri, meskipun tak mudah.
Ah, sayangnya orang-oang kini melihat Indonesia sebagai sebuah asal. Di mana mereka hidup, mencari, dan mati. Sangat sedikit yang memaknainya sebagai sebuah cita-cita. Ya, cita-cita yang di dalamnya termaktub hal-hal universal. Anak-anak muda di awal abad 20 itu sudah memulainya. Mereka menamakannya Manifesto Politik: unity-fraternity-liberty.
Adakah selama ini Indonesia lebih kita fahami sebagai titik berangkat, dan bukan sebagai alamat yang kita tuju? Kalau ya, jangan heran jika yang tampak adalah banyaknya ketidak-sefaaman. Layaknya para musafir di antrean sebuah kereta: berkerumun, tak mengenal satu lainnya, tak berbelas kasih, padahal tujuan mereka satu.
Seperti yang saya yakini di awal: sesuatu yang tidak kita pilihlah yang membentuk diri kita. Tetapi tak banyak orang yang mengerti bahwa apa “yang-tidak-kita-pilih” itu pada akhirnya dibentuk oleh apa yang kita yakini dan kita perbuat. Bagi saya, Indonesia adalah entitas yang belum selesai. Ia akan terus dibangun di atas apa yang kita yakini dan menjelma sebagai entitas bebas dari apa yang kita perbuat. Karena itu, ia seharusnya dimaknai sebagai sesuatu yang “imaginer”, sesuatu yang terus ingin kita gapai.
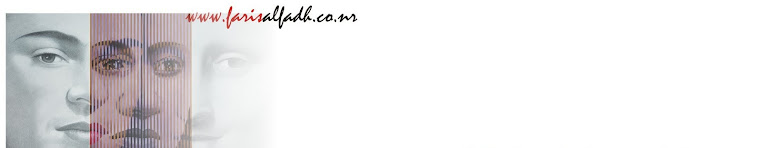



No comments:
Post a Comment