Esai | Faris Alfadh
 Dalam kondisi bangsa yang masih terpuruk, bisa dimaklumi jika banyak orang tak lagi menaruh rasa optimis. Memperingati hari kemerdekaan, tak ada lagi antusias, karena toh semuanya hanya berakhir sebatas seremoni, yang jauh dari harmoni. Namun apa artinya sebuah bangsa tanpa optimisme? Jika dulu Indonesia lahir karena nasionalisme, maka untuk “membesarkannya” ia butuh optimisme!
Dalam kondisi bangsa yang masih terpuruk, bisa dimaklumi jika banyak orang tak lagi menaruh rasa optimis. Memperingati hari kemerdekaan, tak ada lagi antusias, karena toh semuanya hanya berakhir sebatas seremoni, yang jauh dari harmoni. Namun apa artinya sebuah bangsa tanpa optimisme? Jika dulu Indonesia lahir karena nasionalisme, maka untuk “membesarkannya” ia butuh optimisme! Kali ini saya tak akan melupakan sejarah, sebagaimana yang selalu diingatkan Bung Karno. Karena bagaimanapun, sejarah adalah pertauatan waktu yang membentuk masa kini. Seperti kata Khaled Hosseini dalam The Kite Runner, kita tak akan pernah bisa mengubur (sejarah) masa lalu, bagaimanapun ia akan selalu menyeruak mencari jalan keluar. Dan apa yang disebut masa kini, suatu saat pada waktunya, pun akan menjadi sejarah masa lalu.
Saya mencoba membayangkan suatu pagi enam puluh tiga tahun silam. Menjelang pukul 10:00 pada 17 Agustus 1945 itu, di sebuah rumah di jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, sejumlah orang berkumpul. Tak ada gemuruh memang, namun ada sesuatu yang runtuh. Nasionalisme akhirnya meruntuhkan apa yang disebut kolonial. Karena sejak hari itu, semua orang akhirnya tahu, wilayah yang dulunya bernama Hindia Belanda lahir menjadi sebuah entitas yang merdeka dan satu.
“Bangsa Indonesia” pun akhirnya disebut sebagai sebuah identitas. Sebuah radio di bandung kemudian menyiarkan suara Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan untuk pertama kali. Orang-orang pun faham, kini mereka bagian dari revolusi.
63 tahun berselang. Enam presiden telah memimpin negeri ini–empat di antaranya berakhir dengan tidak “hormat”. Banyak yang berubah. Jika dulu kemerdekaan adalah perjuangan melawan yang kolonial, atau setidaknya mengembalikan yang nasional, masih samakah makna itu untuk hari ini? Atau tiap orang memilih maknanya sendiri?
Perubahan datang dengan banyak kemajuan. Namun di Indonesia, hanya sedikit yang berubah. Di antara negara-negara pasca colonial lainnya, Indonesia memang menjadi “big brother” yang lahir lebih dulu– namun sekaligus yang paling terpuruk dan sulit maju.
Kesulitan terbesar Indonesia nampaknya bukan ketika melawan penjajah, tetapi melawan bangsa sendiri. “Perjuangan yang akan kalian hadapi jauh lebih berat,” kata Bung Karno kala itu. “Perjuangan kami hanya melawan penjajah dari luar, sedangkan kalian akan berjuang melawan bangsa sendiri.” Kini kita tahu, ucapan Bung Karno benar.
Tengok saja, berapa rupiah yang dicuri dari alam Indonesia oleh saudara sendiri? Para tauke pun tak ragu menjual pasir di sepanjang kepulauan Riau untuk negara lain. Atau pembalak liar yang menjual kayu dari hutan Kalimantan berkubik-kubik. Serta mereka yang menyelundupkan minyak bersubsidi ke luar negeri, dan membiarkan rakyat antri di dalam negeri. Menghadapi saudara sendiri ternyata membuat kita habis energi. Karena tak tahu dari mana untuk memulai, atau jangan-jangan banyak dari kita yang tak tega hati.
Saya teringat kata-kata Tan Malaka kepada pemerintah Belanda sebelum ia dibuang dulu. Storm ahead!, katanya–ada topan menanti di depan. Don’t’ lose your head! (Jangan kehilangan akal dan kepala!). Justru sebaliknya, adakah kita yang sudah kehilangan akal, untuk sedikit menegakkan kepala di hadapan bangsa lain?
Kemerdekaan? Di tengah selebrasi seremoni, gemuruh nyanyian kemenangan, atau riuh rendah perayaan, adakah yang masih tersisa dari semangat kemerdekaan itu? Bagi saya, kemerdekaan adalah proses yang belum selesai. Seperti sejarah, ia tak akan lekang. Karena kemerdekaan adalah bagian dari masa lalu, kini, dan esok.
Kemerdekaan adalah ketika Indonesia memasuki situasi di mana kita semua (ya, kita semua) bisa duduk nyaman di angkringan dan tidur nyenyak di ranjang. Ketika orang ramai lainnya tak lagi antri mendapatkan minyak tanah. Dan ketika para nelayan tak perlu cemas akan tangkapan esok hari, serta anak-anak mereka yang bisa sekolah dengan riang.
Kemerdekaan adalah ketika politik tak lagi berlangsung dalam amnesia. Ketika kekuasaan tak lagi tergadai oleh para mafia. Dan ketika kita yang berbeda etnis dan agama ini tak lagi khawatir akan konflik dan persaingan, karena semuanya faham akan satu nilai yang mengikat: keindonesiaan!
Dan kemerdekaan? Ya, kemerdekaan adalah ketika tak ada lagi alasan bagi saya dan anda untuk tak hidup bahagia, di tanah air ini. Karena itu, kemerdekaan kali ini tentu menjadi berarti, ketika tanah air yang kita cintai menjadi harmoni, untuk sekedar kita berbagi.
Kemerdekaan? Tentu tak hanya untuk hari ini.
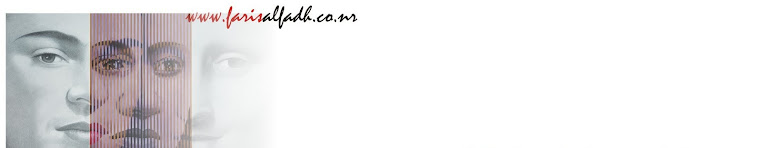



Saya teringat kata-kata Tan Malaka kepada pemerintah Belanda sebelum ia dibuang dulu. Storm ahead!, katanya–ada topan menanti di depan. Don’t’ lose your head! (Jangan kehilangan akal dan kepala!). Justru sebaliknya, adakah kita yang sudah kehilangan akal, untuk sedikit menegakkan kepala di hadapan bangsa lain?
ReplyDeletebagus....kita terjebak dalam euphiroa tanpa makna ya bung
sungguh, aku sempat dibuat merinding ketika membacanya, smoga jiwa itu kian berkobar kawan, salam...
ReplyDelete