Kompas, 3 September 2008
 Kehidupan selalu melahirkan beragam anomali. Tak terkecuali demokrasi. Setidaknya dulu, di Indonesia, demokrasi tak ubahnya otokrasi. Dan kini ia mengaburkan kolonialisasi dan melahirkan oligarki.
Kehidupan selalu melahirkan beragam anomali. Tak terkecuali demokrasi. Setidaknya dulu, di Indonesia, demokrasi tak ubahnya otokrasi. Dan kini ia mengaburkan kolonialisasi dan melahirkan oligarki.
Reformasi 1998 menawarkan fase paling demokrastis dalam sejarah politik
Saat ini negara dan pasar menampilkan konfrontasi paling panas dalam sistem demokrasi liberal. Rezim neolib terus merongrong agar integrasi negara dan pasar bisa terwujud di bawah kendali pasar global. Di negara-negara berkembang seperti
Memang ada politik
Dominasi pasar atas negara menjadikan kapitalisme sebagai panglima dalam praktek demokrasi. Perlahan-lahan negara kehilangan otoritasnya sebagai penyelenggara politik dan digantikan oleh pasar. Sederhananya, jika di negara-negara industri maju negara lah yang menciptakan pasar, maka di negara berkembang, muncul fenomena di mana pasar menciptakan negara. Demokrasi pun menjadi sistem penyelenggaraan negara yang semu, karena semua kendali berada di bawah kuasa modal. Maka tak ada lagi kata yang tepat untuk menandai fenomena ini selain neo-kolonialisme yang sedang berlangsung.
Yang kita saksikan pada tahap selanjutnya tentu saja adalah anomali demokrasi. Di mana demokrasi berharmoni dengan kolonialisasi. Tak ada lagi power, yang ada hanya take-over. Selain itu, disharmoni negara dan pasar juga ikut melahirkan disorganisasi sosial pada tingkat grass-road. Transisi demokrasi tidak mampu lagi melahirkan konsolidasi demokrasi, tetapi konsolidasi aligarki. Bukan revolusi demokratik, tetapi apa yang disebut Miguel Angel Centemo sebagai revolusi teknokratik.
Perlu diingat bahwa sejarah
Fenomena anomali demokrasi di atas pun ikut melahirkan konsekuensi selanjutnya, yakni oligarki demokrasi. Memang munculnya oligarki, di mana kekuasaan dan lembaga-lembaga politik berada di tangan segelintir orang saja, adalah sebuah keniscayaan dan sulit dihindari (immanent). Ilmuwan Robert Mitchel dalam karyanya, Political Parties (1949), menamakannya sebagai hukum besi oligarki (the iron law of oligarchy). Sekali lagi, memang ada gerakan politik
Demokrasi pun lahir sebagai sebuah fenomena yang lebih banyak kita temukan di jalan-jalan
Yang lebih menyakitkan adalah, kehidupan rakyat pada fase demokrasi liberal tidak menawarkan peningkatan kesejahteraan, justru sebaliknya. Ya, demokrasi menjadi sistem politik yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Jika mengacu pada standar PBB, tiap individu dengan 2 dollar perhari, maka lebih dari 50 persen penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 223 juta jiwa tergolong miskin. Yang muncul tentu saja ironi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kekayaan sebesar 75 milyar dollar atau Rp 800 trilyun yang beredar di Indonesia hanya dimiliki oleh 150 orang saja.
Seperti kata Aristoteles, demokrasi adalah sistem politik paling buruk ketika yang tampil sebagai pemimpin adalah golongan masyarakat yang tidak terdidik. Suatu saat, katanya, demokrasi akan memberikan kesempatan bagi lahirnya orang-orang bodoh untuk berkuasa. Mungkin benar, mungkin juga keliru. Karena setiap usaha yang putus asa selalu melahirkan kerinduan akan selapis masyarakat yang hidup dalam komunitas yang cerdas dan bebas. Tapi kini, di Indonesia, demokrasi sedang memperlihatkan pertarungan “orang-orang bodoh.” Berapa banyak anggota parlemen yang masuk bui karena suap dan korupsi?
Di Indonesia demokrasi adalah demonstrasi. Demokrasi memberi peluang berkorupsi. Tetapi demokrasi juga memberikan harapan dan kesempatan untuk kita berdiri sejenak, sekali lagi. Tetapi Demokrasi? “Bah!”, kata penyair Allen Ginsberg. Ya, tanpa persiapan dan pijakan yang kuat, demokrasi barangkali hanya berakhir menjadi mobokrasi!
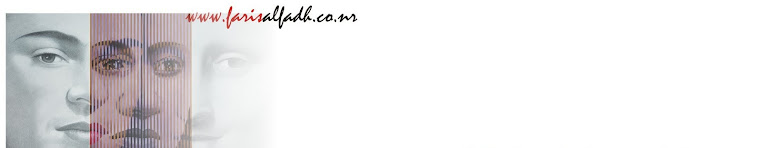



No comments:
Post a Comment