 Dr. Wahidin Sudirohusodo (1857-1917) tidak pernah membayangkan dirinya suatu saat akan dikenang sebagai tokoh kebangkitan nasional. Ketika merintis dan kemudian mendirikan organisasi “Boedi Oetomo” pada tanggal 20 Mei 1908, “dokter Jawa” ini hanya meyakini bahwa hak-hak pribumi harus diperjuangkan.
Dr. Wahidin Sudirohusodo (1857-1917) tidak pernah membayangkan dirinya suatu saat akan dikenang sebagai tokoh kebangkitan nasional. Ketika merintis dan kemudian mendirikan organisasi “Boedi Oetomo” pada tanggal 20 Mei 1908, “dokter Jawa” ini hanya meyakini bahwa hak-hak pribumi harus diperjuangkan.
Sebelum mendirikan Budi Utomo, Wahidin yakin betul bahwa hanya ada satu cara untuk bangkit dari penjajah: memberikan pendidikan kepada pura-putri pribumi. Ia pun mulai mengalang dana pendidikan untuk putra-putri Jawa.
Ide Wahidin akhirnya melampaui pendidikan. Bahwa untuk bangkit tidah cukup hanya dengan pendidikan, tetapi perlu mengambil “jalan politik” dengan menghimpun pribumi-pribumi ke dalam sebuah gagasan persatuan. Bersama rekan-rekannya sesama siswa STOVIA, ia akhirnya mendirikan Budi Utomo sebagai wadah aksi.
Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang lahir di awal abad 20. Walaupun pada awalnya organisasi ini hanya bertumpu pada “ke-Jawa-an”, tetapi dengan segera ia merangkul “Sunda”, “Madura” dan “Bali”. Dalam hal ini Goenawan Mohamad benar, bahwa gerakan politik ke arah keadilan akan selalu terdorong menjangkau yang universal. Ini dibuktikan Budi Utomo. Bahasa yang kemudian digunakan tak lagi Jawa, melainkan Melayu.
Seratus tahun berselang, orang-orang kini mengenang hari lahir Budi Utomo sebagai hari “kebangkitan nasional”.
Tahun ini terasa istimewa, karena genap satu abad. Untuk memperingati 100 tahun kebangkitan nasional tersebut, berbagai acara, talkshow, kuis, bahkan iklan layanan masyarakat ikut mewarnai. Pemerintah pusat bahkan mengadakan pagelaran gegap gempita di Istora Senayan. Saya juga sempat menghadiri beberapa dialog, serta seminar yang khusus diadakan dalam semangat “kabangkitan nasional” ini.
Ide memperingati lahirnya Budi Utomo sebagai hari kebangkitan nasional pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta tahun 1948. Saat itu wilayah teritorial Indonesia masih sangat terbatas. Persoalan muncul karena tekanan dari dalam negeri sendiri serta ancaman serangan dari pihak Belanda. Sepuluh tahun kemudian, 20 Mei 1958, peringatan 50 tahun Budi Utomo kembali diadakan. Saat itu presiden Soekarno mengadakannya di Istana Merdeka dengan meriah. Kini dengan usia satu abad, semangat itu kembali berkobar.
Memperingati 100 tahun kebangkitan nasional, bagi saya masih ada persoalan yang mengganjal. Jika di tahun 1948, memperingati kebangkitan nasional sebagai semangat persatuan untuk membangun Indonesia serta mengatisipasi serangan dari pihak Belanda, dan tahun 1958 karena situasi tanah air yang membutuhkan semangat persatuan, di mana saat itu kondisi beberapa daerah sedang bergejolak, serta ikut menggalang semangat rakyat untuk membebaskan Irian Barat.
Sekarang di tahun 2008 apa yang kita harapkan? Masih perlukah kita berkobar-kobar meneriakkan “bangkit”? Tentu saja kita tidak sedang ingin kembali ke masa lalu seperti yang dikatakan Mona Ozouf, bahwa memepringati suatu peristiwa menunjukkan bahwa kita masih tetap sama seperti dulu dan akan tetap seperti itu pada masa mendatang. Tentu bukan itu maksud kita.
Tidak ada yang salah dengan peringatan 100 tahun kebangkitan nasional. Justru saat ini merupakan momentum paling tepat. Namun yang paling penting adalah kita menyadari betul apa yang sebenarnya kita harapkan untuk bangsa ini. Di akhir tahun 1980-an kita menjadi salah satu negara yang disegani di kawasan Asia, namun tertinggal dari Barat. Kita pun berusaha mengejar Barat.
Di akhir 1990-an kita justru tertinggal dari Asia, kita pun berusaha mengejar negara-negara di Asia. Sekarang jangankan mengejar negara-negara di Asia seperti China, India maupun Korea, kita justru tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan kini kita berada satu level di bawah Vietnam, negara yang dalam dua puluh tahun terakhir masih diselimuti penderitaan akibat perang Vietnam. Saya khawatir jangan-jangan nantinya kita semakin tertinggal dan beralih mengejar Timor Leste.
Jadi, untuk bangkit dibutuhkan tidak hanya sekedar semangat, tetapi juga tekad dan perencanaan. Jika melihat kondisi saat ini, saya khawatir apa yang kita teriakkan sebagai “semangat kebangkitan nasional” akan sia-sia belaka. Tengok saja bagaimana semangatnya kita meneriakkan “Indonesia Bisa”, “Bangkit bangsaku” di berbagai momentum, sementara di luar sana kita membiarkan emas dan minyak bumi kita dicuri orang lain, perusahaan milik negara (BUMN) dibeli pihak asing, jumlah hutang luar negeri kita yang menumpuk, Undang-undang kita yang lebih pro orang asing daripada rakyat sendiri, dan entah apa lagi, yang kesemuanya menyebabkan sebagian besar dari mayarakat kita harus menanggung kerugian.
Kebangkitan seperti apa yang bisa kita harapkan dari kondisi seperti ini? Maka jalan satu-satunya untuk bangkit adalah: selamatkan kekayaan yang kita miliki, dan bangun kesadaran bahwa kemandirian lebih penting dari sekedar untung sesaat. Karena hanya dengan inilah kita bisa membangun kembali sendi-sendi masyarakat yang sebagian telah runtuh.
Semangat dan kepercayaan diri itu penting, tetapi semangat yang terejawantahkan dalam kesadaran nasionalis dan strategi jauh lebih penting. Seharusnya pemerintah pasca-reformasi menyadari hal ini sedari dulu. Bahwa untuk bangkit, dibutuhkan sikap kemadirian. Membiarkan orang lain yang tak dikenal masuk ke dalam rumah kita tentu beresiko kehilangan sebagian barang yang kita miliki.
100 tahun kebangkitan nasional, satu hal lagi yang diperlukan: optimisme bahwa Indonesia belum habis! Karena Indonesia adalah project yang belum selesai.
Faris Alfadh

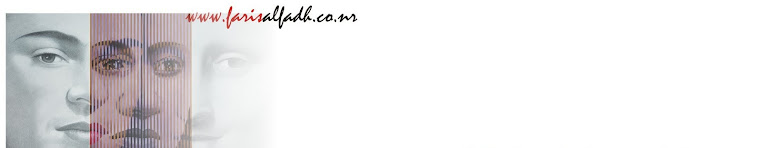



No comments:
Post a Comment