
Republika, 03 Agustus 2011
Tidak pernah ada yang menduga bahwa teror bom dan letusan puluhan mesiu jatuh di atas tanah Norwegia, negara yang selama ini dianggap paling aman, di mana semangat demokrasi, keterbukaan, dan kesetaraan begitu dihormati.
Tragedi ini tidak hanya menyisakan pilu bagi masyarakat Norwegia, tetapi sekaligus duka kemanusiaan bagi kita semua. Bagi Norwegia, aksi brutal yang dilakukan Anders Behring Breivik merupakan kejahatan paling buruk yang pernah terjadi sejak Perang Dunia II. Karena itu, PM Stoltenberg menyebutnya sebagai satu tragedi nasional. Sedangkan bagi sebagian besar dari kita, ini seperti rongrongan yang terus berupaya menyanyikan kidung kematian bagi setiap dialog kemanusiaan.
Tragedi yang terjadi di Kota Oslo dan Pulau Utoya tersebut semakin menegaskan bahwa asumsi yang selalu mengaitkan aksi teror dengan tradisi bangsa atau agama tertentu adalah keliru, terutama kampanye-kampanye besar yang selama ini diteriakkan AS, yang dalam banyak hal terkadang semakin mendiskreditkan Islam. Teror tidak pernah lahir dari nubuat agama.
Tariq Ali, dalam The Clash of Fundamentalisms: Crusade, Jihads and Modernity (2002), mengajak kita untuk melihat perbedaan sumir antara ajaran agama dan praktik para penganutnya. Apa yang terjadi selama ini, terutama upaya menarik agama dalam spektrum kekerasan, tidak lebih dari eksploitasi para penganut agama atas motif-motif tertentu. Agama memang kerap dijadikan dalil, namun kita pun mafhum bahwa agama manapun menolak keras semua jenis kejahatan yang memusnahkan manusia.
Karena itu, walaupun Anders Behring Breivik menyebut dirinya seorang fundamentalis Kristen dan menulis manifesto politik setebal 1.500 halaman yang sebagian isinya bernada anti-Islam, aksi teror yang ia lakukan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama Kristen. Begitu juga aksi-aksi lain yang dilakukan kelompok-kelompok Islam radikal.
Aksi teror bisa dipahami sebagai unjuk rasa simbolis atas ketidakpuasan terhadap produk regulasi ataupun perilaku politik dan ekonomi. Dalam kasus Norwegia, kita melihat bagaimana alasan-alasan kekhawatiran terhadap multikulturalisme, kekecewaan terkait kebijakan imigran, serta ketakutan yang berlebihan telah menyeruak. Di AS, aksi seperti ini pernah terjadi di Oklahoma pada tahun 1995, yang menewaskan 168 orang.
Eropa pernah mengalami sejarah yang cukup panjang terkait radikalisme dan kekerasan, yang secara gamblang menempatkan agama dalam jarak yang tegas. Selama 1960-an dan 1970-an, misalnya, terorisme dikaitkan secara samar-samar dengan kelompok ekstrem sayap kiri. Keadilan sosial menjadi kata kunci aksi. Karena itu pula mengapa faham politik seperti Marxisme mendapat perhatian. Pada 1980-an dan 1990-an, pola terorisme mulai bergeser ke kelompok ekstrem sayap kanan. Ideologi ultranasional dan fanatisme atas ras menyeruak sebagai pembenaran.
Perubahan signifikan dalam memandang kekerasan dan teror terjadi pascatragedi 9/11 seiring propaganda "war on terrorism" yang dilakukan AS dan sekutunya, terutama upaya politik yang secara brutal semakin menyudutkan kelompok Islam radikal serta menarik agama sebagai sesuatu yang fundamental dalam kejahatan teror. Stigma negatif yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam seolah menegaskan bahwa agama menjadi sumber malapetaka.
Teror di Norwegia seperti lonceng yang seolah membangunkan kesadaran negara-negara Eropa dan AS, yang selama lebih dari satu dekade hanya fokus pada kelompok-kelompok Islam radikal serta menjustifikasi agama (baca: Islam) sebagai sumber kekerasan, namun melupakan potensi yang bisa hadir dari kelompok-kelompok domestik.
Selama ini, AS memang berhasil memenangi diskursus terorisme global dan mengambil keuntungan dari itu. Namun, hal tersebut juga harus dibayar mahal, terutama terkait dua hal. Pertama, kebijakan utilitarian AS, seperti yang dilakukan di Irak, Afghanistan, dan beberapa negara berpenduduk Muslim, yang semakin menumpuk kebencian dari kelompok-kelompok Islam. Hal ini tak pelak mendorong munculnya aksi-aksi kekerasan yang sebenarnya bukanlah hadir atas nama Tuhan, melainkan balasan atas ketidakadilan yang sudah hadir secara historis.
Kedua, kebijakan AS dan sekutunya juga turut andil dalam memupuk kebencian dalam kelompok-kelompok ekstrem sayap kanan di AS dan beberapa negara Eropa terhadap Islam dan penduduk Muslim diaspora. Bagi Eropa yang sejak dulu sudah menghadapi fenomena migrasi, termasuk dari penduduk negara Muslim, mulai merasa terancam. Stigma negatif yang begitu kuat dilekatkan terhadap kelompok Islam semakin memperbesar rasa tidak aman.
Apa yang terjadi di Norwegia setidaknya menjadi catatan penting, yakni teror bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh seorang individu. Namun perlu diingat bahwa politik yang dibangun atas rasa kebencian bisa membimbing siapa pun yang terkucilkan dan diliputi amarah untuk menerobos jalan kekerasan.
Faris Alfadh
image from here
Mahasiswa Hubungan Internasional UMY Raih Prestasi di Ajang SUKARABIC FEST
VII 2025 Tingkat Asia Tenggara
-
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY), Abdulsalam Saad, kembali menorehkan prestasi membanggakan
sete...
1 month ago
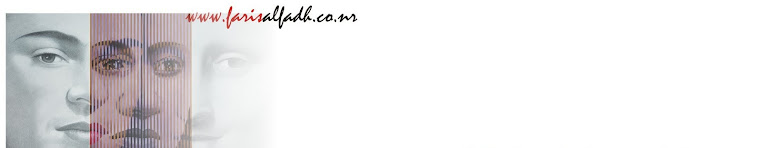



No comments:
Post a Comment